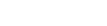Guru yang Merdeka Mengajar dengan Cinta
Merdeka dalam mengajar adalah tampak dari keikhlasannya saat menjalankan peran sebagai guru. Menjalankan peran dengan penuh cinta dan ketulusan.
Saat lagi capek-capeknya menghadapi anak-anak yang remidi, tiba-tiba ingat dengan ucapan mbah Moen tentang bagaimana seharusnya seorang guru ketika mendapati anak didiknya yang masih kesulitan belajar.
Jadi guru itu tidak usah punya niat bikin pintar orang, nanti kamu hanya marah-marah Ketika melihat muridmu tidak pintar. Ikhlasnya jadi hilang. Yang penting niat menyampaikan ilmu dan mendidik yang baik. Masalah muridmu kelak jadi pintar atau tidak, serahkan pada Allah, didoakan saja terus menerus agar muridnya mendapat hidayah.
Memang benar, selama ini ketika ada siswa yang nilainya belum mencapai KKM, maka kita akan merasa bahwa itu semua adalah kesalahan siswa. Sebagai guru kita telah merasa melakukan yang terbaik, mulai dari penyampaian materi, pemilihan bobot soal yang diujikan, maupun segala macam alasan lainnya. Namun pada kenyataannya, tetap saja ada anak-anak yang remidi. Akhirnya kita akan merasa capek dan terkadang marah terhadap si anak, baik itu kita lakukan secara langsung dihadapan si anak, maupun secara diam-diam (terkadang membicarakannya dengan teman sekantor, atau ada juga yang memilih untuk memendamnya dalam hati)
Jika kita menyadari bahwa tugas kita sebagai guru adalah sebatas menyampaikan dan mendoakan, maka niscaya tidak akan merasa kesal dan marah jika masih ada anak yang remidi. Jika saja kita menyadari bahwa mengajar anak-anak yang disertai dengan keikhlasan adalah sebuah ibadah yang memiliki nilai sangat tinggi disisi Allah, maka kita tidak akan merasa rugi saat harus mengulanginya berapa kalipun.
Kalau saja kita meyakini bahwa saat kita melakukan kegiatan belajar mengajar adalah saat dimana para malaikat menggunakan sayapnya untuk memberi naungan bagi kita, seluruh makhluk dilaut dan di bumi berdoa dan memohonkan ampun untuk kita, serta padanan yang Allah berikan kepada kita adalah menimbang tinta-tinta yang kita keluarkan setara dengan darah para syuhada, niscaya tidak akan pernah ada drama dan ungkapan-ungkapan “Haduh….dia lagi….dia lagi….selalu remidi….”
Kembali pada dawuh mbah Moen diatas, tugas guru selain Ikhlas dalam mendidik adalah mendoakan…nah, untuk yang ini kita kerap melalaikannya. Lupa menyertakan nama anak-anak didik kita dalam doa-doa yang kerap kali kita panjatkan. Padahal seandainya kita menyebut mereka dalam doa-doa kita, maka Allah akan bentangkan “tali” yang akan menghubungkan kita dengan si anak, dimana pada gilirannya nanti akan melahirkan sebuah ikatan yang tidak akan lekang walau mereka sudah keluar dari sekolah. Bahkan pada tataran yang lebih jauh lagi, insyaAllah “tali” tersebut akan menjadi salah satu penyebab dientaskannya kita dari neraka, dan ditarik menuju surga Allah. Bisakah kita bayangkan, betapa bahagianya ketika kita sedang menderita di neraka, tiba-tiba ada tangan yang menarik kita, dan setelah kita melihatnya, dia adalah salah satu anak didik kita di dunia.
Ada sebuah kisah yang sangat menarik, dimana jika kita cermati maka kisah ini bisa menjadi pelipur lara ketika sebagai guru maupun orangtua merasa gagal dalam mendidik anak. Kisah indah ini dinukil dari manusia terbaik dan guru terhebat sepanjang masa, Rasulullah Shallallahu alaihi Wasallam, yang disajikan dengan sangat indah oleh Salim A. fillah dalam Lapis-Lapis Keberkahan.
Suatu saat Aisyah bertanya kepada Rasulullah “ Wahai Rasulullah, peristiwa apa yang menurut engkau lebih berat daripada perang Uhud?” lantas Rasul menjawab, bahwa dakwah beliau ke Thoif adalah sebuah peristiwa yang jauh lebih berat bagi beliau disbanding perang Uhud.
“ Aku pergi dengan kegundahan dalam hati, hingga tiba di Qarn Ats-Tsa’alib. Ketika kuangkat kepalaku, maka tampaklah Jibril memanggilku dengan suara yang memenuhi ufuk. “Sesungguhnya Rabb mu telah mengetahui apa yang dikatakan dan diperbuat kaummu terhadapmu. Maka Dia mengutus malaikat penjaga gunung ini untuk kau perintahkan sesukamu”
“Lalu malaikat penjaga gunung menimpali “ya Rasulallah, ya Nabiyallah, ya Habiballah, perintahkanlah, maka aku akan membalikkan gunung Akhsyabain ini agar menimpa dan menghancurkan mereka yang telah ingkar, mendustakan, menista, mengusir dan menyakitimu”
Dan lihatlah jawaban yang keluar dari lisan yang mulia. Padahal Allah sudah menawarkan hal yang sangat menggiurkan untuk melampiaskan rasa kecewa yang membuncah di dada. Jawaban yang sungguh tidak akan mungkin keluar dari manusia biasa.
“ Tidak, sungguh aku ingin agar diriku diutus sebagai pembawa Rahmat, bukan penyebab azab. Bahkan aku ingin agar dari sulbi-sulbi mereka, dari Rahim-rahim mereka, kelak Allah akan keluarkan anak keturunan yang mengesakan-Nya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun”
Mengapa Rasulullah memilih peristiwa diatas sebagai sebuah kisah yang lebih berat daripada perang Uhud? Padahal dalam perang Uhud pelipis beliau terluka oleh 3 cincin besi, lutut beliau juga terluka, 70 sahabat setia gugur dan paman tercinta wafat dalam kondisi mengenaskan. Bukankah perisitiwa itu sudah sangat menyedihkan? Akan tetapi bagi Rasulullah penolakan atas dakwah di Thoif jauh lebih menyedihkan.
Ternyata sedihnya beliau adalah karena rasa cinta yang begitu besar kepada ummatnya. Melihat penolakan dan perlakuan mereka, sudah terbayang bahwa Allah pasti akan murka kepada mereka. Maka seperti halnya seorang ibu ketika membayangkan hal buruk akan menimpa anak-anaknya, pasti akan merasa sedih.
Hal lain yang perlu dicermati adalah, Rasulullah tidak putus asa dengan kondisi tersebut. Bahkan doa-doa terbaik tetap terkirim untuk para manusia “durhaka” ini, dimana jika bukan mereka yang jadi baik, minimal anak keturunan merekalah yang akan jadi manusia-manusia beriman.
Menghadapi penolakan itu, Rasulullah bahkan sempat mengakui kelemahan dirinya dalam berdakwah. Dengan mengucapkan doa berikut
“ Allahumma ya Allah, kepada- Mu aku mengadukan kelemahanku, kekurangan daya upayaku dihadapan manusia. Wahai Tuhan yang Maha Rahim, Engkaulah Tuhan orang-orang yang lemah dan Tuhan pelindungku. Kepada siapa Engkau hendak serahkan nasibku? Kepada orang jauhkah yang berwajah muram kepadaku atau kepada musuh yang akan menguasai diriku? Asalkan Engkau tidak murka kepadaku, aku tidak peduli, sebab sungguh luas kenikmatan yang Engkau limpahkan kepadaku. Aku berlindung kepada nur wajah-Mu yang menyinari kegelapan dan karena itu yang membawa kebaikan di dunia dan akhirat dari kemurkaan-Mu dan yang engkau timpakan kepadaku. Kepada Engkaulah akua dukan halku sehingga Engkau Ridha kepadaku. Dan tiada daya Upaya melainkan dengan kehendak Mu”
Sungguh sangat indah, betapa ketika Rasulullah merasa tidak mampu menyampaikan tugasnya berdakwah, beliau tidak mencari alasan dengan menyalahkan penduduk Thoif, namun justru mengakui bahwa salah satu penyebabnya adalah karena “kelemahan” beliau, dan saat itu juga beliau melibatkan Allah untuk menutupi kegundahan hatinya.
Jika dikaitkan dengan perasaan kita saat meremidi anak-anak kita, bukankah kita juga merasakan kesedihan yang sama saat anak-anak tidak menguasai apa yang telah kita sampaikan? Merasa dikhianati dan disepelekan saat kita melihat angka-angka yang berkisar pada ukuran nomor sepatu tertera di lembar-lembar ujian mereka? Bukankah rasanya akan sangat memuaskan saat kita mengeluhkan tentang si A yang selalu remidi dan teman kita menimpali dengan ucapan “bener banget….si a memang kaya’ gitu, disaya juga remidi…”
Bahkan terkadang kepada si anak, kita dengan “murah hati” melontarkan kalimat “kamu tidak akan jadi apa-apa jika terus seperti ini….” Sebuah kalimat yang mungkin bagi kita saat mengucapkannya terasa biasa saja, namun bagi beberapa hati yang menerimanya akan terasa sebagai hunjaman pedang yang menancap ke ulu hati. Tidakkah kita berpikir bahwa ucapan itu juga nantinya akan dihisab? Bagaimana jika karena ucapan itu maka seorang anak akan melabeli dirinya sendiri dengan label negatif dan terbawa sampai kehidupannya selepas sekolah? Dan bayangkan jika kelak dihadapan Allah, si anak berkata “ya Allah, aku seperti ini karena ucapan salah satu guruku yang meragukan bahwa aku bisa menjadi manusia baik”
Pernahkah terlintas dalam pikiran kita, bahwa kegagalan itu juga salah satu penyebabnya adalah karena kelemahan kita? Atau justru kita tetap bersikukuh bahwa “saya sudah berupaya secara maksimal, dianya aja yang kurang fokus dan semacamnya”
Tiba-tiba terdengar suara yang sangat pelan dari diri sendiri, yang ditujukan kepada diri sendiri pula
“Baru juga meremidi… sudah gak sabar. Padahal anak-anak juga sudah nurut, gak marah-marah, gak mengusir apalagi melempar batu. Mengajar dan remidinya juga di kelas yang tidak panas, gak perlu jalan kaki jauh-jauh, dapat ijaroh pula. Lihatlah Rasulullah yang harus menempuh perjalanan 100 km dalam cuaca panas, berjalan kaki, beliau tawarkan ajakan untuk keselamatan, tidak dibayar dengan materi, malah ditolak, dihina, diusir, dilempari batu dan bahkan diancam untuk dibunuh”
“Gitu kok ngaku warsatul anbiya’….jangan ngaku-ngaku hanya pada tinggi derajatnya saja tapi gak mau mengikuti susahnya” timpal suara lainnya.
Akhirnya, kita akhiri tulisan ini sampai disini, karena suara-suara lainnya akan semakin banyak bermunculan.
At least, semoga Allah mengaruniakan kesabaran kepada kita dalam mendidik anak-anak dan dari amal yang sedikit itu, Allah terima dan menjadi penolong kita di hadapan Nya. Aamiin…ya Robbal alamiin…
Kamal, 12 Agustus 2023
26 menit menjelang deadline.
Fitriya Zulianik (Guru SMK)
pemenang lomba menulis kreatif tingkat guru dan karyawan bertema Kemerdekaan yg diselenggarakan YPAS