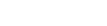5 Juli, 1938.
“Ikut...berperang?”
“Iya, aku berencana untuk ikut berperang membela tanah air kita. Bagaimana menurutmu?” Dari dalam sebuah ruangan terdengar suara dua orang yang sedang berbicara. Yang jika didengar lebih teliti lagi, maka yang berbicara adalah seorang wanita dan pria. “...Kamu..kamu yakin?” Suara halus tadi kembali berbicara. “Aku yakin. Sangat yakin.” Mendengar jawaban semangat itu, sang puan hanya bisa menghela nafasnya dan tersenyum kearah sang wira. “Yasudah jikalau kemauanmu begitu. Aku tak akan melarangmu, Sagara.” Nama lelaki yang sedang berbicara dengannya sekarang—Sagara. Putra Sagara.
“Tapi kamu janji akan...kembali ke dekapanku, kan?” Sagara tersenyum lalu memeluk erat sang wanita tercintanya. “Tentu saja. Aku pasti akan kembali dengan bangga padamu. Cahya-ku.” Cahya—atau dengan nama asli Drisana Cahyaningrum—memeluk Sagara kembali. “Baiklah kalau begitu. Aku akan menunggumu disini.” Cahya tersenyum kecil. Sedangkan Sagara menganggukkan kepalanya pelan.
“Jadi...kapan kamu akan berangkat? Dan kira-kira kapan kamu akan kembali?” Cahya kembali bertanya. Sagara tampak ragu untuk menjawab, tapi kemudian ia menjelaskan, “Rencananya, aku akan berangkat dua minggu lagi. Tentang kira-kira kapan aku akan pulang....” Sagara menggelengkan kepalanya pelan. “Aku tak tau dengan pasti. Maafkan aku.”
Mendengar penuturan itu, senyum di wajah Cahya semakin menghilang. Ia pasti akan menangis jika saja Sagara tidak segera memeluknya dan berkata, “Kau tidak perlu khawatir, karena aku adalah orang terkuat di desa, bukan?” Ia berucap dengan suara lantang dan jenaka, kebiasannya sejak dulu jika ia sedang gugup. Tangan Cahya mencengkram punggung dari orang terkasihnya itu, berharap bisa menahan Sagara untuk berada tetap di pelukannya. Namun keputusan suaminya sudah bulat, ia akan pergi dua minggu lagi, dan pulang entah kapan. Mungkin juga ia tidak akan kembali.
Pikiran untuk melanjutkan hidup tanpa Sagara disisinya semakin mengganggu Cahya. Air matanya tidak dapat ditahan lagi, dan isak demi isakan keluar dari antara dua jiwa itu. Menahan mereka untuk menahan satu sama lain lebih lama lagi.
Sagara mengusap ujung kepala Cahya dengan lembut. “Jangan khawatirkan aku. Aku pasti kembali untukmu.” Tangis Cahya mereda secara perlahan. Cahya menganggukkan kepalanya. Melihat itu Sagara tersenyum dan melepaskan dekapannya pada tubuh Cahya. “Bagaimana jika ku kirimkan surat untukmu tiap hari? Agar kamu tau bagaimana kabarku di medan perang nanti.”
“Tentu. Aku akan dengan senang hati menerima semua suratmu.” Cahya terkekeh sembari menghapus air matanya yang sempat mengalir dengan deras tadi. “Kalau begitu, ayo mulai kemas-kemas barang yang akan kamu bawa nanti.” Cahya tersenyum kepada Sagara.
19 Juli,1938.
2 minggu telah berlalu dengan cepat bagi Sagara dan Cahya. Tidak terasa, tapi hari itu adalah hari di mana Sagara akan pergi meninggalkan Cahya untuk pergi berperang. Pasangan suami-istri itu sedang berjalan berdampingan menuju pintu depan rumah mereka. Tidak ada yang bersuara, hingga mereka sampai tepat di depan pintu masuk utama.
“Jadi..aku berangkat ya?” Sagara bertanya dengan kekehan kecil sembari memutar balikkan tubuhnya untuk melihat sang terkasih lebih jelas. Cahya hanya menganggukkan kepalanya dan tersenyum simpul. Hatinya terasa sangat berat untuk melepaskan Sagara pergi. Ia takut jika Sagara tidak akan kembali ke sisinya setelah perang usai. Tapi apa daya, Keputusan suaminya sudah bulat. Dan Cahya tak akan pernah bisa melarangnya untuk ikut terjun ke medan perang.
Tak mendengar jawaban apa pun dari Cahya, Sagara mengulum senyum kecil di bibirnya lalu memeluk sang puan secara tiba-tiba. Perlakuan Sagara tadi membuat Cahya terkejut meskipun hanya sedikit. “Sampai jumpa, istriku Drisana Cahyaningrum. Do’a kan agar aku selamat ya.” Sagara membisikkan kalimat tadi tepat di depan telinga Cahya. Membuat Cahya tak bisa membendung air mata yang sejak tadi ia tahan. Isak demi isakan kecil mulai terdengar dari kedua insan yang sedang berpelukan itu. Sagara terkekeh. Ia mengusap punggung Cahya perlahan, mencoba menenangkan sang wanita yang sekarang tengah menangis dipelukannya.
“Kamu pasti kembali kan?” Ditengah-tengah suara isakan tadi, Cahya bertanya kepada Sagara. Meskipun Ia tau ia sudah menanyakan hal ini berulang-ulang kali, tapi ia yakin Sagara tak akan pernah bosan untuk menjawab pertanyaannya yang satu ini. Dan jawaban yang Sagara lontarkan selalu sama, “Tentu saja. Tunggu aku pulang ya?” Dekapan Sagara makin mengencang. Ia sebenarnya juga tak tega meninggalkan istrinya sendirian dirumah. Tapi ia tetap harus pergi.
Lima menit telah mereka habiskan untuk berpelukan, merasakan kehangatan satu sama lain untuk yang terakhir kalinya sebelum Sagara pergi. Dengan sangat perlahan Sagara melepaskan pelukannya dari tubuh Cahya. Karena ia tau bahwa ia harus segara berangkat. Meskipun ia sendiri masih merasa tak puas berpelukan dengan wanitanya.
Cahya tersenyum dan berkata, “Kamu pasti bisa. Aku yakin kamu pasti bisa kembali dengan selamat. Dan,” Cahya mengangkat tangan kanannya dan menangkup pipi Sagara. “Jangan lupa untuk mengirimkanku surat. Tolong jaga kesehatanmu ya.” Sagara kerkekeh. Ia melepaskan telapak tangan Cahya yang terletak di pipinya lalu mundur selangkah. Ia berlutut layaknya seorang prajurit kepada Cahya sambil berujar, “Baiklah, yang mulia ratu. Akan hamba usahakan. Dan sang prajurit ini berjanji untuk pulang dengan selamat ke sisi anda, Ratuku.” Sagara mengucapkan kalimat tadi dengan nada yang tegas. Layaknya seorang prajurit jika sedang berhadapan dengan atasannya. Cahya tertawa pelan, merasa sedikit terhibur dengan ucapan Sagara. “Jaga dirimu baik-baik. Jangan lupa untuk makan dan istirahat dengan teratur, jaga kesehatanmu juga. Kamu mengerti istriku?” Diakhir kalimat yang ia lontarkan, Sagara menggunakan nada jenaka. Mencoba agar perpisahan ini tak hanya diisi dengan kesedihan dan tangis.
Cahya tersenyum lalu mengangguk. “Tentu saja.” Mendengar itu Sagara ikut tersenyum kearah Cahya. Ia mulai berjalan melewati pekarangan rumahnya. Namun, selang beberapa langkah dari pintu depan rumah mereka, Sagara membalikkan badannya kembali. Hal itu tentu saja membuat Cahya bingung. “..Ada barang yang tertinggal kah?” Cahya memiringkan kepalanya kesamping. Melihat reaksi itu, Sagara hanya terkekeh dan menggelengkan kepalanya. “Ada sebuah kalimat yang belum kuucapkan. Dan hal itu adalah,”
“Sampai jumpa, Cahyaku.” Dengan begitu Sagara langsung membalikkan badannya dan mulai berjalan kembali. Jauh dan semakin menjauh. Hingga bayangannya tak tertangkap oleh mata Cahya sama sekali.
30 November 1938.
Sudah hampir lima bulan Sagara pergi berperang. Meninggalkan Cahya sendirian dirumah mereka. Hari-hari selalu Cahya lewati dalam sunyi dan sepi. Biasanya selalu ada Sagara yang membantunya atau hanya sekedar bertukar kata dengannya. Namun, semua itu hanya bisa ia kenang sekarang. Cahya tau bahwa ini pasti terjadi. Sendirian dirumah, tanpa ada yang mengajaknya berbicara ataupun membantunya membersihkan rumah.
Cahya menghela nafasnya. Ia meletakkan sapu yang ia pegang ke dinding lalu duduk di tempat tidur miliknya dan Sagara. Ia melihat ke sekeliling kamarnya. Hanya ada dirinya disini, tak ada orang lain. Sunyi adalah hal yang selalu menemaninya sejak Sagara pergi. Kembali ia lihat cerminan wajahnya di cermin besar yang terletak di meja. “Wajahku tidak berubah sama sekali...hanya saja—” Cahya menangkup kedua pipinya sendiri. Memperhatikan bentuk wajahnya dengan lebih detail. “Kantung mataku semakin menebal ya.” Cahya menghela nafasnya lagi. Memang akhir-akhir ini ia sering sekali kesulitan untuk tidur. Kelopak mata miliknya seperti melarang Cahya untuk tertidur lebih awal. Bukan akhir-akhir ini sebenarnya, namun sejak dua bulan yang lalu. Cahya juga tidak tau kenapa, tapi sebelum tidur ia selalu merasa cemas akan sesuatu. Terkadang Cahya berpikir bahwa rasa cemasnya ini ada kaitannya dengan Sagara. Ia berpikir bahwa rasa cemas ini terjadi karena pikirannya tentang Sagara yang tak akan kembali, atau lebih buruk lagi—Sagara telah meninggal.
Cahya menepis semua pikiran negatif tentang kemungkinan yang terjadi pada Sagara dan memutuskan untuk merebahkan tubuhnya di tempat tidur yang sekarang ia duduki. Cahya melihat kearah langit-langit kamarnya. Tanpa ia sadari perlahan-lahan kelopak matanya mulai tertutup. Sampai akhirnya terdengar suara dengkuran halus dari kamar yang ia tempati sekarang.
14 Juli 1940.
Hari ini berjalan seperti biasanya bagi Cahya. Tak ada yang special meskipun tepat dua hari lagi adalah ulang tahunnya yang ke 22. Ia sedang melakukan rutinitas paginya sekaranng. Seperti membuka jendela depan agar udara di dalam rumahnya tidak terlalu panas, dan menyapu halaman sekaligus menyiram bunga yang ada dipekarangannya.
Setelah selesai dengan rutinitas paginya, Cahya segera masuk kembali ke dalam rumahnya. Lagipula, tak ada yang bisa ia lakukan lagi diluar. Saat didalam, Cahya segera mengecek jam yang terletak dimeja tempat pajangan-pajangan fotonya. Jam 10.00 alias tepat jam sepuluh pagi. “Aku masih ada waktu untuk beristirahat sejenak sepertinya. Pekerjaanku juga sudah selesai...” Tanpa pikir panjang, Cahya segera berjalan kearah kamarnya, berencana untuk mengambil sedikit waktunya untuk tidur sejenak.
Tok tok tok..
Baru saja Cahya sampai di kamarnya, ia tiba-tiba mendengar suara ketukan pintu. Dengan segera Cahya berjalan cepat—sedikit berlari mungkin—ke bagian ruang tamu. Jantungnya berdegup dengan kencang. Sebenarnya Cahya sendiri juga bingung kenapa jantungnya berdegup tak karuan setelah mendengar suara ketukan pintu tadi. Apa mungkin karena Cahya berpikir bahwa yang mengetuk pintunya tadi adalah Sagara? Mungkin saja. Saat sampai di depan pintu, Cahya segera membuka pintunya dan hampir saja mengucapkan nama Sagara jika saja orang yang mengetuk pintunya itu tidak langsung menyapanya.
“Selamat siang, nona. Apa benar ini dengan nona Drisana Cahyaningrum?” Cahya terdiam ditempat. Ada sedikit perasaan kecewa dalam diri Cahya dikarenakan ternyata yang mengetuk pintunya tadi bukanlah Sagara. Melainkan seorang pria berumur sekitar tiga puluh lima sampai empat puluh-an yang sedang membawa sebuah surat ditangannya. “Nona? Nona, apa anda mendengar saya? Apa perlu saya ulangi?” Lamunan Cahya seketika buyar, ia bahkan tidak menyadari bahwa ia telah terdiam dan melamun semenjak orang itu berbicara padanya.
“Ah..maafkan saya. Sejenak saya kira yang mengetuk pintu rumah saya tadi adalah suami saya.” Cahya menundukkan kepalanya malu. Tapi memang apa yang telah ia ucapkan adalah kenyataan. “Jika anda berkenan, mungkin anda bisa mengulangi perkataan anda barusan.” Pria itu tersenyum. “Tentu saja nona. Saya tadi hanya bertanya, apa benar nama anda adalah Drisana Cahyaningrum?” Sang pria menguangi kalimatnya yang tadi tak didengar oleh Cahya. Mendengar itu, Cahya segera menganggukkan kepalanya. “Kalau begitu.. surat ini untuk anda. Nona Drisana.” Pria itu menjulurkan surat yang sedari tadi ia pegang. Surat dengan warna coklat dan sedikit lusuh. Tanpa ragu, Cahya segera mengambil suratnya dan seketika terkejut saat membaca nama sang pengirim surat itu.
“Tugas saya disini telah selesai. Kalau begitu, saya akan pergi sekarang. Sampai jumpa nona.” Dan dengan begitu pria tadi pergi. Dan Cahya langsung masuk kedalam rumahnya. Tak sabar untuk membaca surat pertama yang dikirimkan oleh Sagara.
Hatinya sangat menggebu-gebu untuk membaca surat yang yang dikirimkan oleh suaminya ini. Sudah dua tahun sejak Sagara pergi. Dan baru kali ini Cahya menerima surat darinya. Tentu saja hal itu membuat Cahya sangat tak sabaran untuk mengetahui bagaimana keadaan Sagara sekarang. Tanpa basa-basi lagi, Cahya segera membuka surat itu dan membacanya dengan sangat perlahan.
Untuk sang laksmiku di rumah.
Jika adinda menerima surat ini, maka aku telah tiada. Aku tau kamu sudah mencoba untuk menghalangiku agar tidak ikut di medan perang ini. Tetapi, jika bukan aku lantas siapa? Siapa yang akan membela negara kita?
Maaf, aku sepertinya tak bisa menepati janjiku padamu Cahyaku. Aku ingin, tapi takdir berkata sebaliknya.
Aku sudah mengirimkan beribu-ribu surat kepadamu, tapi tampaknya adinda satu ini tidak pernah membalasnya ya? semoga saja semua surat-surat itu sampai dengan selamat ke tanganmu.
Namun, aku harap surat yang satu ini tak akan pernah terkirim kerumah kita. Melainkan aku yang akan sampai dengan selamat lalu mendekapmu dengan sangat erat. Tapi apa daya? Jikalau engkau sudah membaca semua ini. Berarti aku sudah tidak ada.
Cukup sampai disini saja isi suratnya, Cahyaku. Aku harap kita bisa bertemu kembali suatu saat nanti. Tot we elkaar weer ontmoeten, mijn licht. Sampai jumpa lagi, sayangku
—Dari prajurit yang senantiasa mencintaimu. P. Sagara
Senyum di wajah Cahya memudar setelah membaca seluruh isi surat tadi. Tanpa ia sadari, air mata meluncur begitu saja di pipinya. Tapi Cahya sama sekali tak memiliki niat untuk memberhentikan tangisannya sekarang. Seketika kepalanya terasa seperti terombang-ambing. Kepalanya pusing, dan ia langsung jatuh terduduk begitu saja dengan memegang erat surat dari Sagara yang baru saja ia baca.
“Yang benar saja...tidak tidak tidak. Ia pasti kembali. Sagara sudah berjanji padaku bahwa ia akan kembali dengan bangga. Apa ini..” Kembali ia baca surat itu dengan lebih teliti lagi. Namun, isinya tetap sama. Tak ada yang berubah. Hatinya terasa seperti ditusuk beribu-ribu pisau. Rasa cemasnya sekarang benar-benar terjadi. Cahya mencoba untuk berdiri, tapi gagal. Ia mencoba berdiri sekali lagi, tapi kali ini dengan bersandar pada tembok sebagai tumpuannya. Namun hasilnya tetap gagal. Ia kembali terduduk lemas di lantai. Kepalanya terasa amat sangat berat. Sampai akhirnya, Cahya memutuskan untuk menyerah dan beristirahat disana saja.
***
Kini hari-hari Cahya terasa semakin sepi. Harapan untuk bertemu dengan Sagara kembali dan melanjutkan hidup dengannya sudah pupus sejak ia mendapatkan surat dari sang wira tiga bulan lalu. Sering sekali Cahya tampak diam termenung menatap surat dan foto-foto lama Sagara yang ia punya. Cahya tau ia harus mulai merelakan kepergianya, tapi hatinya tak bisa. Tak jarang juga Cahya menangis secara tiba-tiba sebelum ia tidur. Kehilangan Sagara sangat berdampak padanya. Tapi ia juga harus menepati janjinya pada Sagara untuk tetap menjaga kesehatannya.
Sore ini, kembali ia baca surat pemberian Sagara. Sudah puluhan kali—atau mungkin ratusan—Cahya membaca suratnya, sampai-sampai ia hafal mati dengan isi dari surat itu. Bahkan, terkadang Cahya tampak berbicara kepada angin kosong. Padahal hal yang sedang ia lakukan adalah membalas surat dari suaminya itu secara lisan.
Namun, seketika dahi Cahya berkerut dikala ia menyadari sesuatu ketika membaca beberapa kalimat yang tertera didalam sang surat. ‘Aku sudah mengirimkan beribu-ribu surat kepadamu, tapi tampaknya adinda satu ini tidak pernah membalasnya ya? semoga saja semua surat-surat itu sampai dengan selamat ke tanganmu.’ Cahya kembali membaca ulang kalimat tadi, sekarang dengan lebih perlahan. Terutama dibagian, ‘Aku sudah mengirimkan beribu-ribu surat kepadamu.’
“Apa maksudmu dengan telah mengirimkan beribu-ribu surat padaku..Sagara?” Kerutan di dahi Cahya makin terlihat dengan jelas. Ia bingung luar biasa sekarang. Pasalnya, seingat Cahya ia tak pernah menerima satu pun surat dari Sagara—kecuali surat yang ia dapatkan tiga bulan yang lalu.
22 Juni 1946.
Sudah enam tahun sejak Cahya mendapatkan satu surat terakhir hari Sagara. Ia sudah mulai menjalani kehidupannya seperti biasa. Bahkan, tampaknya Cahya sudah merelakan kepergian Sagara. Seperti sore ini, Cahya sudah menyelesaikan semua pekerjaan rumahnya yang sempat tertunda. Ia sekarang tengah duduk dihalaman depan rumahnya sembari menyesap secangkir teh hangat. Semilir angin yang cukup sejuk berhasil menerbangkan beberapa helaian rambutnya yang panjang itu.
Sekarangpun Cahya sibuk menikmati keindahan taman yang ada didepannya saat ini, sampai-sampai ia tak mendengar suara langkah kaki yang mulai mendekat kearahnya.
“Permisi, nona Drisana.” Mendengar namanya dipanggil, Cahya segera menoleh kearah sampingnya. Sejenak Cahya memperhatikan wajah dari pria yang tadi memanggil namanya. Wajahnya tampak familier bagi Cahya. Ia tampak berpikir sejenak, Cahya sangat yakin jika ia pernah melihat wajah pria ini. Tapi ia lupa dimana tepatnya.
Pria paruh baya itu tampak tersenyum kearah Cahya. “Nona pasti merasa familier dengan wajah saya. Apa tebakan saya benar?” Pria itu terkekeh, sedangkan wajah Cahya tampak sedikit terkejut karena tebakan pria itu benar. “Saya adalah orang yang mengirimkan sebuah surat kepada anda sekitar..enam tahun yang lalu.” Dan dengan kalimat itulah Cahya akhirnya mengingat kenapa wajah pria ini tampak familier baginya.
“Berarti anda kemari karena ingin memberikan sebuah surat yang dikirimkan untuk saya. Benar?” Cahya bertanya kepada sang pria lalu terkekeh pelan. Sang pria memberikan anggukan sebagai respon atas pertanyaan Cahya. “Benar sekali. Namun, kali ini surat yang ingin saya berikan kepada anda bukan hanya satu saja. Melainkan, puluhan surat.” Wajah Cahya tampak terkejut untuk sepersekian detik saja.
“Puluhan surat.. untuk saya?” Tanya Cahya. Ia tak percaya dengan ucapan sang pengirim surat yang sekarang sedang berdiri tepat dihadapannya. “Benar sekali nona. Saya disini bertugas untuk mengantarkan puluhan surat yang tertuju pada Drisana Cahyaningrum. Dan orang itu adalah anda.” Pria itu mengeluarkan tiga map besar bewarna coklat dan menyerahkannya kepada Cahya. “Silahkan nona. Semua surat ini ditujukan kepada anda.”
Dengan perlahan-lahan Cahya menerima tiga lembar map besar itu. Dan setelah yakin bahwa map itu selamat sampai di tangan Cahya, sang pria langsung saja pamit undur diri. “Kalau begitu, saya akan pergi sekarang nona.”
***
Sudah tiga hari sejak Cahya menerima puluhan surat dari seseorang. Tapi sampai sekarang ia masih belum berani untuk membuka surat-surat itu sama sekali. Ada sedikit perasaan takut yang menghantuinya. Tapi sebagian dirinya juga penasaran, siapa nama dibalik pengirim puluhan surat-surat itu.
Cahya menghela nafasnya. Ia sudah membulatkan keberaniannya untuk membuka atau sekedar membaca nama dari sang pengirim surat. “Ayo Cahya. Kamu pasti bisa. Apa yang kamu takutkan?”
Cahya berjalan kearah meja dimana map berisi surat-surat itu ia letakkan. Sejenak terlintas dipikiran Cahya untuk membukanya besok saja. Tapi ia segera menepis pikiran itu. “Ayu Cahya. Membaca beberapa surat tak akan membunuhmu, Cahya.” Cahya sedang mencoba untuk meyakinkan dirinya lagi. Kembali ia tarik nafas dalam-dalam, sebelum ia hembuskan dengan perlahan. Tangannya mulai meraih map coklat itu. Dan jari-jemarinya bekerja untuk membuka ikatan pada map coklat itu. Dan hal pertama yang ia sadari ketika melihat surat itu adalah nama sang pengirim. Matanya membulat sempurna.
“...Putra Sagara..? Surat surat ini dikirim oleh...Sagara?” Dengan tergesa Cahya mulai mengeluarkan tiap surat yang ada didalam map coklat yang sedang ia pegang sekarang. Entah kenapa, ia merasakan secerah harapan setelah membaca nama dari sang pengirim surat itu. Cahya memperhatikan surat-surat itu dengan lebih seksama. Sampai ia melihat sebuah angka yang tertulis di bagian ojok kiri atas paad setiap surat. “Ini pasti tanggal saat Sagara membuat surat ini...”
Cahya segera mengurutkan tanggalan yang ada pada surat-surat itu. Dan surat dengan tanggalan paling lama ialah surat dengan kode angka 30/07/1938. Bulan yang sama saat Sagara baru pergi untuk berperang. Tanpa pikir panjang, Cahya membuka surat itu dan membacanya perlahan.
30/07/1938.
Halo istriku. Bagaimana kabarmu? Maaf aku baru bisa menuliskan surat ini sekarang. Aku benar-benar sibuk dengan masalah disini. Oh, sepertinya sampai disini dulu saja isi suratnya. Sampai jumpa di lain surat, Cahyaku.
—P.Sagara
Setelah membaca kalimat terakhir dari surat pertama, Cahya membuka mulutnya untuk menjawab pertanyaan dari Sagara di dalam surat tadi. “Kabarku baik, Sagara. Bagaimana denganmu?” Cahya terkekeh mendengar penuturannya sendiri. Cahya melipat surat pertama tadi lalu langsung mengambil surat kedua untuk ia baca selanjutnya.
05/08/1938.
Cahyaku, hari ini aku hampir saja tertembak peluru. Tapi, tentu saja aku selamat. Sudah kubilang, kamu tidak perlu mengkhawatirkan aku. Aku ini pria terkuat di desa kita. Baik, sampai disini dulu suratnya.
—dari suami tercintamu yang hampir tertembak tadi.
Cahya bingung ia harus bereaksi seperti apa sekarang. Ia khawatir saat membaca kalimat dimana Sagara hampir tertembak peluru. Namun, ia juga ingin tertawa saat membaca nama pengirim yang Sagara tulis diakhir surat. Cahya melipat surat yang baru saja ia baca lalu mengambil satu surat random dari tumpukan surat-surat miliknya itu.
12/01/1939.
Tak terasa ya, tapi sudah tujuh bulan kita terpisah. Sepertinya aku mulai meridukanmu..dan aku yakin kamu pasti juga merindukanku. Tenang saja. Aku pasti kembali.
Oh iya, hari ini kami berhasil menghancurkan salah satu benteng musuh. Hebat bukan? Tentu saja, lagipula ada aku yang membantu mereka. Haha, aku hanya bercanda.
—dari prajurit bernama P.Sagara.
Cahya tak bisa menahan rasa bangganya pada Sagara sekarang. “Hebat sekali. Tentu saja semua itu bisa tercapai karena adanya kamu disana.” Cahya tertawa ketika mendengar penuturannya barusan.
***
Sudah hampir satu jam lebih Cahya duduk sembari membaca dan menanggapi satu persatu surat yang dikirim oleh Sagara. Yang tak Cahya sadari ialah bagaimana raut wajahnya berubah berkali-kali setiap ia membaca satu surat. Terkadang ia akan tertawa, lalu tiba-tiba ia akan cemas dan khawatir. Puluhan surat sudah ia baca. Hingga sampailah ia pada dua surat terakhir. Senyum pada wajah Cahya mulai pudar disaat ia melihat bahwa surat yang belum ia baca hanya tersisa dua. “Hanya tersisa dua surat ya..” Dengan sangat perlahan Cahya mulai membaca surat dengan nomor kode 05/05/1940.
05 Mei 1940.
Rencana kami gagal. Banyak diantara kami yang gugur, bahkan tak sedikit juga yang mengalami luka berat. Tempat persembunyian kami juga sudah diketahui oleh mereka. Dan ternyata, ada salah seorang dari kami yang bekerja sama dnegan musuh. Sungguh keterlaluan.
Maaf, sepertinya surat ini tak akan terlalu panjang. Aku harus segera bergerak kembali sampai jumpa.
—P.Sagara.
Seketika itu juga jantung Cahya berdegup dengan sangat kencang. Rasa cemasnya meningkat. Hanya tersisa satu surat lagi. Dan Cahya tak mungkin tidak membaca surat yang terakhir. Cahya menarik nafasnya terlebih dahulu. Mencoba menetralkan degup jantungnya yang tak karuan. “Satu surat lagi Cahya. Hanya satu..” Cahya mengangkat surat dengan kode angka 28/06/1940. Dengan perasaan berat ia mulai membuka surat itu dan membacanya.
28 Juni 1940.
Kami benar-benar gagal. Semuanya telah gugur. Hanya tersisa diriku dan pimpinan kami. Namun, sepertinya keberntungan sama sekali tidak berpihak pada kami. Aku dan pimpinan kami terpisah. Namun aku sudah menitipkan sesuatu untukmu padanya. Sepertinya ini akan menjadi surat terakhirku...Sampai jumpa. Aku mencintaimu, selalu.
—Prajurit Bernama P.Sagara.
Tanpa Cahya sadari, air mata lolos begitu saja melewati pipinya tepat ketika ia selesai membaca surat terakhir yang ditulis oleh Sagara. Cahya menangis. “Begitu rupanya...aku bangga padamu, Sagara. Sungguh. Aku sangat bangga padamu. Lihatlah sekarang. Negara kita sudah merdeka. Jasamu akan selalu dikenang.” Cahya berusaha sekuat tenaga untuk menunjukan senyum terbaiknya. Ia harus tetap tegar. Sama seperti Sagara yang selalu tegar disetiap situasi. “Aku harap kamu tenang sekarang, Sagara.”
***